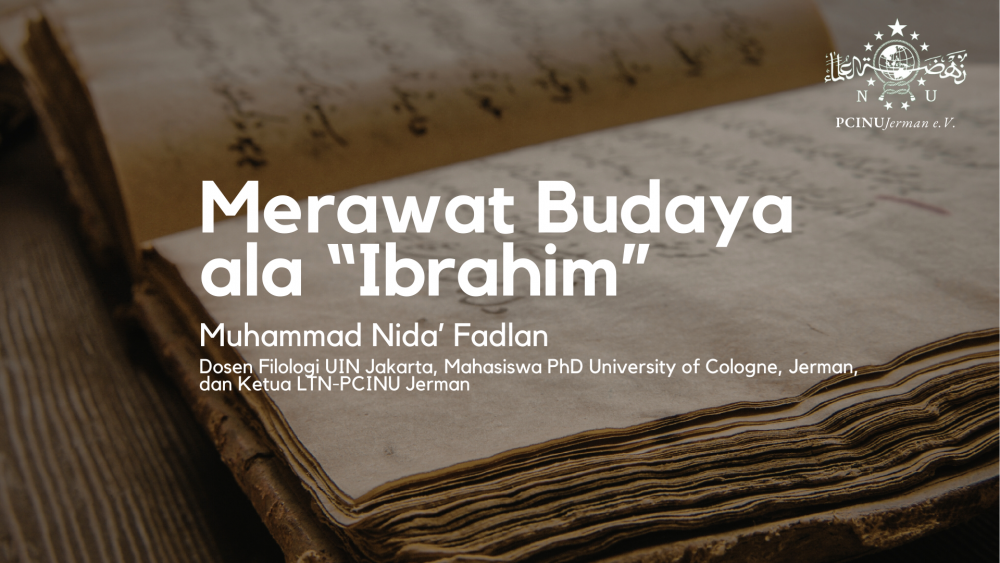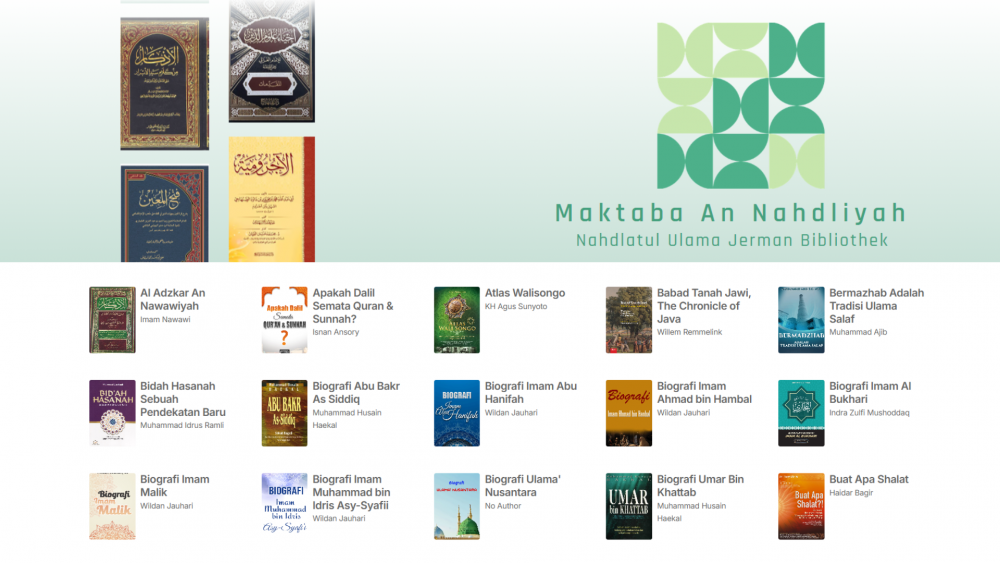Oleh: Zacky Khairul Umam
Islam tradisional, yang di negeri kita terwakili secara dominan oleh Nahdlatul Ulama, tidak pernah memiliki satu pandangan politik yang tunggal. Ini adalah pernyataan telak untuk menyangkal sebuah pandangan dari luar bahwa NU, misalnya, itu satu.
Dari beberapa kawan dan ilmuwan Muslim yang belajar Islam di kampus Barat namun juga belajar dengan ulama tradisional di Timur Tengah, saya belakangan mengakrabi istilah yang mereka namakan dengan ‘neo-tradisionalisme’. Sebagai neo-tradisionalis, mereka mengikuti empat mazhab hukum Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi`i, atau Hanbali), berteologi Asy`ari atau Maturidi, dan juga mengikuti sufisme. Sama dengan NU bukan?
Perbedaannya ialah pada sikap politik. Ketika tokoh Mesir ternama Syekh Ali Gomaa dan ualam UEA Habib Ali al-Jifri mendukung pemerintahan militer di Mesir setelah revolusi Arab 2011, bahkan cenderung membiarkan (dalam beberapa analisis lebih keras lagi bahasanya: ikut mendorong) pembantaian Rabi`a yang banyak memakan korban pendukung al-Ikhwan al-Muslimun, mereka mengeluarkan kritik yang cukup menampar. Kritiknya, jika tak salah lihat, sebetulnya ialah perpanjangan nalar dari maqasid syari`ah yang dalam dunia kontemporer dihidupkan oleh para ‘pembaharu’ pemikiran Islam.
Begitupun dengan ulama kharismatik Suriah, Syekh Ramadan al-Buti, yang dibunuh oleh pemberontak Asad, juga satu tarikan nafas dengan sikap Ali Gomaa itu. Syekh Abdallah bin Bayyah, seorang ulama Mauritania di Jeddah, dan juga jaringan internasional lain seperti Hamza Yusuf di Amerika, juga satu barisan.
Dalam kategori ilmu sosial, barisan ini dimasukkan dalam quietisme politik, cenderung diam soal politik dan mendukung rezim yang berkuasa. Barangkali jika dilacak lebih mendalam ini erat terkait dengan doktrin politik Sunni klasik untuk patuh dan taat serta menyaratkan stabilitas politik demi keberlangsungan kekebasan beribadah. Tentu saja, membangkang atau bughat tidak diperbolehkan. Sementara kalangan neo-tradisionalis dikategorikan ke dalam Sufi politik. Mereka kritis terhadap penguasa, yang bersandar pada contoh klasik yang menentang kolonialisme dan kezaliman. Biasanya mereka merujuk pada Salahuddin al-Ayyubi (dinasti Ayyubiah, abad ke-12), Usman dan Fudio (abad ke-18 di Nigeria), atau Abdal Qadir al-Jaza’iri (Aljazair abad ke-19). Mereka biasanya lupa atau tidak kenal dengan figur Syekh Yusuf al-Makassari (abad ke-17), tapi tak mengapa karena nama ini belum seterkenal figur Sufi ‘pemberontak’ lainnya. Sebabnya banyak, bukan pembahasan kali ini.
Jangan salah sangka! Pengikut neo-tradisionalisme, seperti di dalam lingkaran Syekh Abdal Hakim Murad di Cambridge (anehnya saya kurang tahu apakah Syekh Husamuddin Meyer di Frankfurt punya pandangan politik serupa), ini masih sangat menghormati ulama tradisionalis betapapun pandangan politik mereka berseberangan. Neo-tradisionalis bagaimanapun ialah penerus tradisionalis yang salah satu prinsipnya dalam belajar agama ialah mencari sanad dari ulama yang masih hidup sehingga keilmuannya bersambung tak terputus hingga masa lalu, hingga ke Kanjeng Rasulullah yang dibimbing langsung oleh Gusti Allah. Islamisme dan Salafisme dengan ragam variannya masih menjadi rival dan saingan mereka dalam menentukan otoritas keagamaan di era modern ini.
Yang diinginkan dari neo-tradisionalisme bahwa perbedaan pendapat di dalam tubuh Sunnisme itu ialah keniscayaan, tak dapat ditolak. Jika begini, sama dong dengan sikap NU sebetulnya? Saya berspekulasi, jika saja kalangan militer di Mesir tidak membunuh dengan membabi buta kalangan oposisi mereka, tidak akan muncul reaksi keras dari neo-tradisionalis.
Para figur neo-tradisionalis ini, persoalannya, kebanyakan hidup di Barat. Jadi mereka bisa menjaga jarak dengan penguasa diktator di negeri muslim dan tetap kritis. Apakah jika mereka hidup di Mesir misalnya mereka akan bersuara keras? Ini pilihan politik yang sulit, tergantung pada nyali, keberanian, dan dukungan massa. Soal kejernihan moralitas politik tak bisa ditawar tentu saja. Di negeri Barat juga bisa menjadi sasaran kritik yang empuk. Walaupun melek tradisi politik Barat dengan baik, sikap mereka atas LGBT dianggap tidak terlalu liberal meskipun mereka tetap menyuarakan toleransi. Posisi mereka yang ‘netral’ di Barat akan bertumbuh pesat, soalnya mereka menciptakan generasi baru yang tetap mencari akar keilmuan tradisional Islam dengan sanad tapi tetap menjaga spirit kritisisme.
Bagaimana dengan tradisionalisme di negeri kita tercinta? Perlu ditekankan dulu bahwa situasinya bisa berbeda dan tidak selalu sama, tapi ada garis yang sama. Karena medan perlawanan yang sama, yakni melawan Islamisme yang semakin kentara efeknya di dunia sosial-politik, maka dalam taraf tertentu apa yang dilakukan Sisi atas al-Ikhwan diterima. Kampanye dialog antaragama dan perdamaian di Dubai yang disokong oleh kalangan tradisionalis ikut disokong. Acara serupa di Mesir pun sama, sebab al-Azhar masih menjadi kiblat bagi Sunnisme.
Di dalam tradisionalisme NU, ‘NKRI harga mati’ sebelum periode 2014 ke sini adalah bahasa biasa untuk hubbul watan min al-iman. Sebagian besar dari kalangan ini masih beranggapan serupa, walaupun bisa disalahgunakan oleh pemerintah saat ini. Tentu ada aspek pragmatisme politik yang digunakan sebagian individu atau lembaga untuk memainkan bandul politik antara pemerintah dan masyarakat demi meraih kemaslahatan dalam ruang kenegaraan yang lebih besar. Saya sendiri, dalam beberapa hal, memaklumi hal ini.
Yang agak ganjil ialah cara memandang yang dominan atas konflik dan masyarakat di Timur Tengah di dalam tubuh (sebagian) nahdiyyin. Satu contoh yang kerap terulang ialah bahwa konflik Timur Tengah timbul begitu saja, tanpa aspek kritik atas kolonialisme, dan perpecahan yang terjadi di kawasan itu jangan sampai diimpor ke dalam negeri kita. Walhasil, tradisionalisme kita cukup efektif terus dijadikan sapi perah pemerintah lagi dan lagi untuk menghadang kelompok yang anti-NKRI. Sebetulnya, saya harus jujur, tidak bisa kategori tradisionalisme Timur Tengah yang dikritik neo-tradisionalisme (global) itu plek sama dengan situasi di tanah air, karena – ini yang sering diabaikan kalangan Islam politik dan Salafi – kalangan tradisionalis NU sudah cukup lama dan berpengalaman menjadi pihak yang terpinggirkan. Untuk berubah menjadi neo-tradisionalis terdepan, syarat mutlaknya ialah penguatan ekonomi dan kemandirian jam`iyyah yang di era Reformasi digemakan sebagai ‘masyarakat madani’ yang kuat! Saat ini saja yang kritis banyak, apalagi kalau kuat ya...
Catatan: bedakan dengan tradisionalisme Seyyed Hossein Nasr dengan sophia perennis-nya