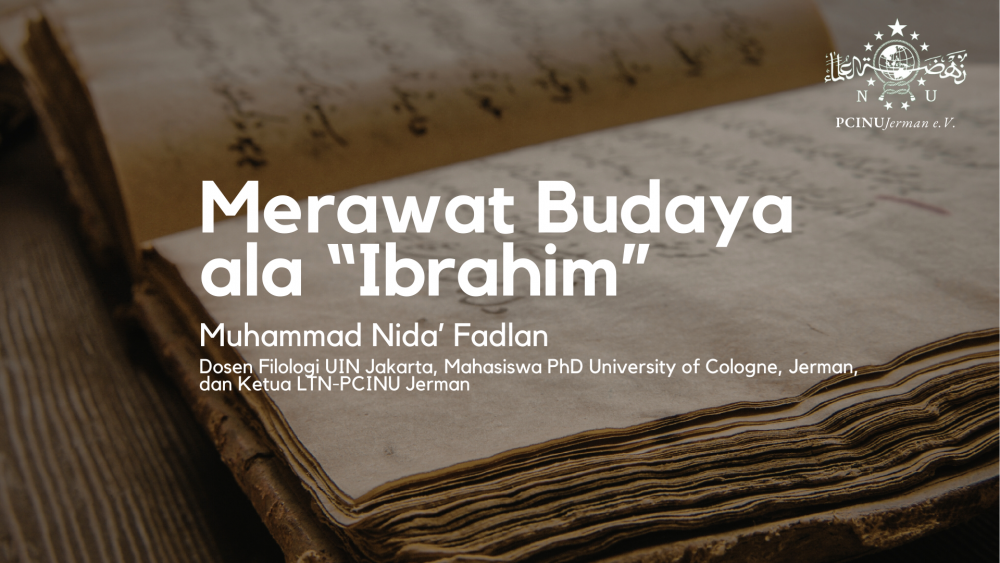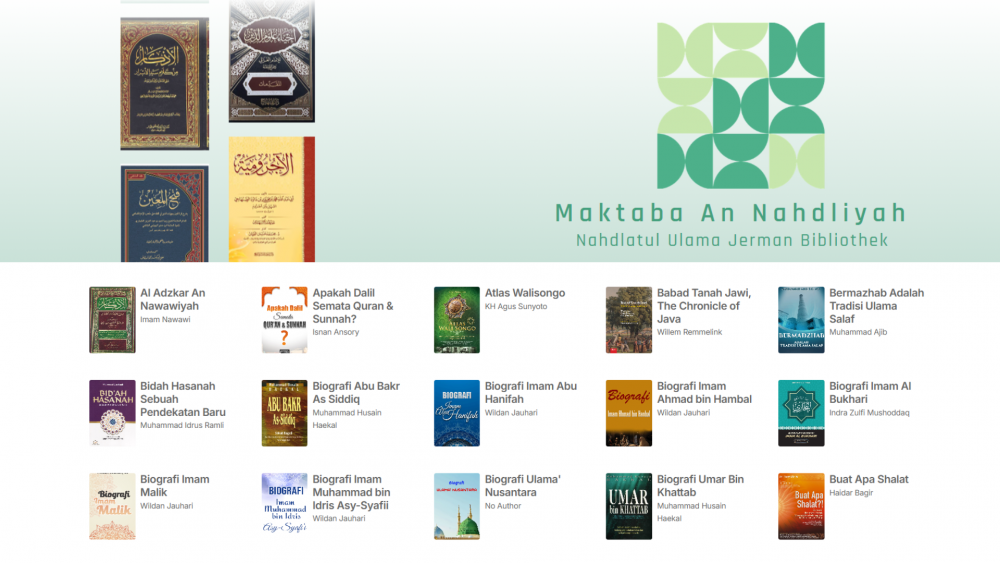Oleh Munirul Ikhwan*
Seperti biasanya masjid Kufah ramai dipadati jamaah yang datang untuk belajar Islam atau hanya sekedar mendengarkan ceramah atau cerita-cerita hikmah dari para da’i (wu’adh) atau penceramah (qushshash). Bagi para pencari ilmu, tentu saja halaqah (lingkaran majlis) seorang ‘alim (jamak: ulama) menjadi tujuan utamanya. Namun, bagi jamaah kebanyakan, halaqah penceramah adalah halaqah yang paling favorit. Mendengarkan ceramah atau cerita bagi mereka seakan-akan lebih penting daripada sepotong roti. Zur’ah al-Qashsh adalah salah seorang penceramah favorit yang biasa membuka majlis di masjid Kufah. Kemampuan retorikanya mampu menarik perhatian jamaah secara luas.
Dikisahkan bahwa pada suatu saat ibu Imam Abu Hanifah (m. 150/767) bimbang perihal hukum suatu perkara. Mengetahui hal tersebut, Abu Hanifah yang dikenal sebagai pendiri madzhab fiqih Hanafi memberikan fatwanya (pandangan hukum). Namun, ibunya menolaknya, meragukan kebenaran pandangan putranya tersebut. Abu Hanifah tahu bahwa ibunya biasa menghadiri majlis ceramah Zur’ah. Lantas, ia mengantarkan ibunya untuk bertemu Zur’ah. “Ini ibuku. Ia ingin meminta fatwamu tentang suatu masalah,“ kata Abu Hanifah. Zur’ah pun terkaget dan berkata, “Wahai Abu Hanifah! Engkau lebih tahu dan lebih pakar daripada aku. Engkau saja yang memberi fatwa ibumu!” Abu Hanifah menjawab, “Aku sudah menyampaikan pendapatku. Namun, ibuku menolak hingga kamu memberikan fatwamu.” Zur’ah berkata kepada ibu Abu Hanifah, “Pendapatku sama dengan pendapat putramu.” Setelah mendengar jawaban tersebut, ibu Abu Hanifah baru menerima pendapat putranya.
Kisah di atas mengilustrasikan loyalitas orang awam terhadap penceramah agama. Namun, loyalitas tersbut bahkan mampu mengalahkan kepercayaan terhadap kompetensi ‘alim, yang notabene mempunyai kualifikasi keilmuan lebih tinggi dari penceramah agama. Penceramah agama menjadi daya tarik bagi orang awam karena retorikanya yang mampu menyentuh emosi dan psikologi orang kebanyakan. Orang awam —yang malas secara intelektual—kurang/tidak tertarik dengan narasi epistemologis ulama; mereka lebih tertarik dengan retorika penceramah dan kisah-kisah yang mampu memvisualisasikan nilai-nilai abstrak agama. Perlu diketahui bahwa dikotomi ‘alim-penceramah bukanlah dikotomi yang ketat, karena ada di antara ulama yang juga mampu melakukan fungsi sebagai penceramah, dan mendapatkan banyak pengikut dari aktivitas ceramahnya tersebut.
Revolusi dan demokratisasi media komunikasi dewasa ini membuka ruang-ruang baru bagi diskursus keagamaan. Agama tidak lagi jenak bertahan di ruang-ruang konvensional seperti masjid dan madrasah, namun sudah merambah ke ruang-ruang baru yang lebih ‘sekular’ seperti cafe, taman, radio, televisi dan internet. Munculnya diskursus agama di ruang-ruang publik baru tersebut tidak lepas dari peran aktor-aktor baru yang mampu “mengkoreografikan” agama di ruang-ruang baru tersebut. Di ruang publik, agama tentunya tidak lagi menjadi monopoli ulama. Orang dari berbagai latar belakang pendidikan, profesi, dan afiliasi mulai terbuka membincang apa itu Islam dan bagaimana Islam berperan dalam kehidupan masyarakat Muslim. Di situlah Islam publik muncul.
Di era revolusi media di mana popularitas berimbas pada keuntungan kapital, tidak heran jika penceramah atau ustadz ‘selebritis’ muncul dan sering menghiasi moment dan event keagamaan. Masyarakat awam yang mempunyai kapital intelektual terbatas sementara ghirah (semangat) keagamaan sedang tinggi membutuhkan media untuk merasakan “sensasi” agama. Di sinilah kelebihan penceramah; mereka mampu membuat yang transendental menjadi sensable (dapat dirasakan). Perlu diingat bahwa yang transendental itu tidak mampu menampakkan dirinya sendiri (self-revealing); sebaliknya ia butuh proses mediasi agar dapat dirasakan oleh publik. Dalam hal ini, penceramah dengan retorika, isyarat, koreografi tertentu mampu “mensensasikan” yang transendental.
Lantas, apakah ulama dan penceramah harus terlibat dalam relasi kontestasi, atau mungkinkah mereka saling bekerja sama? Banyak pihak menginginkan relasi ideal, yaitu keduanya dapat saling bekerja sama. Ulama menggali hukum dengan kemampuan intelektualnya dengan merujuk sumber-sumber ‘otoritatif’, sementara penceramah menyampaikan temuan-temuan epistemik ulama kepada masyarakat luas dalam bahasa populer. Namun, formasi ideal ini tak selalu berjalan sebagaimana dikehendaki. Di era kebebasan berpendapat, orang awam pun berani bersuara siapa yang masuk dalam kategori ulama dan siapa yang bukan. Kontestasi antara ulama dan penceramah tentu saja bukan fenomena yang unik di era modern. Imam Jalal al-Din al-Suyuthi (m. 911/1505) pernah terlibat polemik dengan —dan mendapat ancaman dari— para penceramah gara-gara kritiknya terhadap mereka yang sering mengutip hadits yang tidak shahih untuk menjaga loyalitas jamaah.
Tampaknya, fragmentrasi otoritas agama menjadi jadi diri Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad Saw. Islam tidak mempunyai institusi resmi untuk menentukan sumber-sumber kanonik dan doktrin-doktrin agama. Ulama yang menjadi pewaris Nabi pun sering tidak sepakat dalam banyak hal. Di era modern, revolusi media komunikasi dan demokratisasi mengintensifkan fragmentrasi ini. Tesis Talal Asad, seorang antropolog Islam, barangkali ada benarnya bahwa Islam adalah tradisi diskursif, dan ortodoksi di dalam Islam ditentukan oleh relasi kuasa.
* Rois Syuriah PCINU Jerman (2014-2015), dan dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta