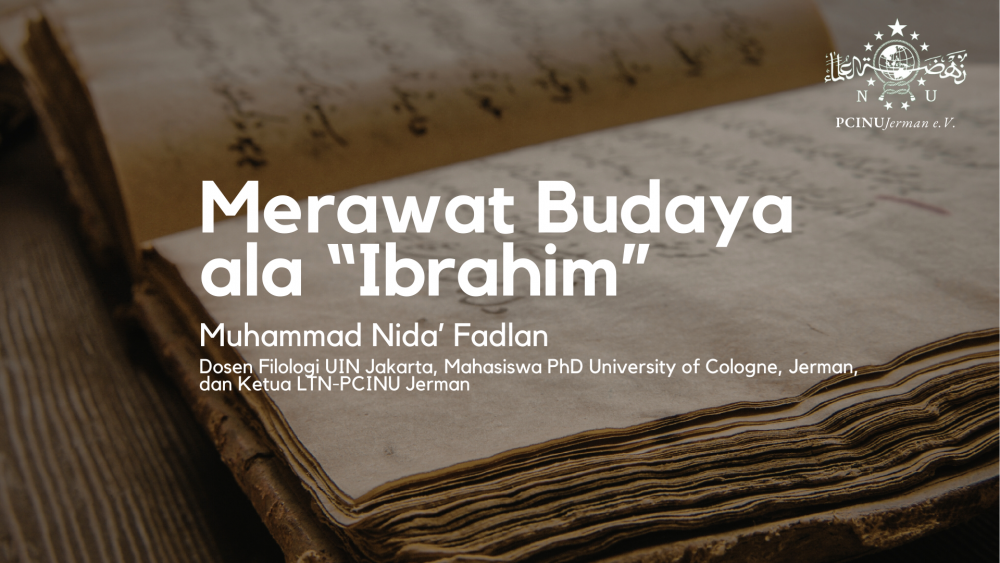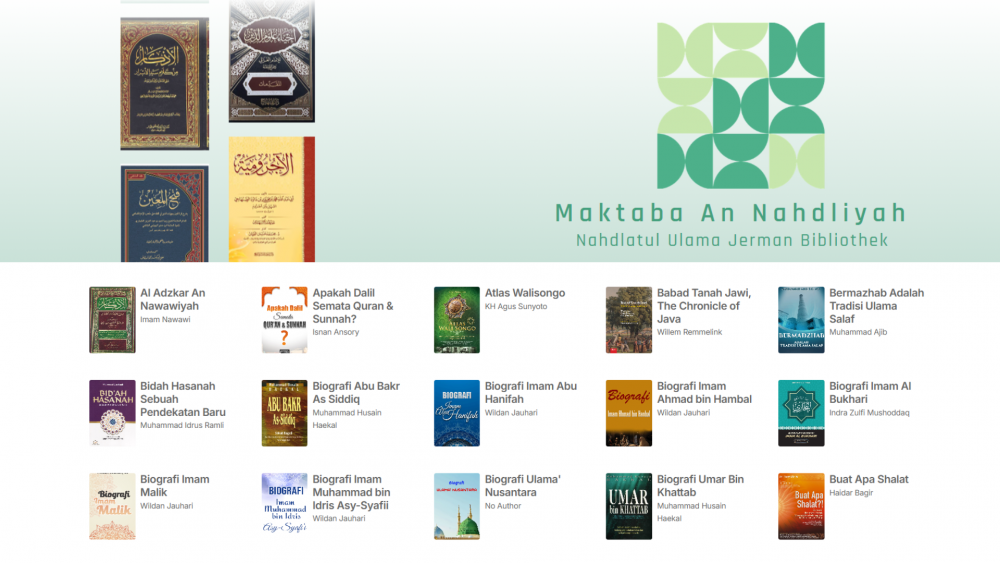Awal tahun 2026 ini, masih adakah optimisme bahwa kapal kita menuju peradaban yang lebih baik? Sebagai jamaah NU yang saat ini belajar dan bekerja di Jerman, saya sering memandang Indonesia dari jarak yang memberi ruang untuk kontemplasi. Berada di luar Indonesia ternyata memungkinkan melihat negeri ini dari sudut pandang berbeda, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memberikan refleksi bersama: sebuah negeri kaya potensi, salah satu dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, namun seringnya masih kesulitan memahami dan menerapkan nilai agama sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan inklusif.
Faktanya, birokrasi belum sepenuhnya efektif, sistem belum terintegrasi, apatisme meningkat, praktik-praktik negatif masih marak, dan kebijakan sering gagal menyentuh kehidupan para pencari nafkah sehari-hari. Upaya mengatasi persoalan bangsa seringkali terasa seperti menambal tembok yang bocor: masalah tidak diselesaikan dari akarnya, energi habis untuk saling menyalahkan atau menggantungkan solusi pada figur tertentu. Padahal, Indonesia memiliki nilai gotong royong sebagai fondasi, tetapi nilai itu memudar ketika sistem yang keliru dibiarkan tanpa pembenahan. Kita seperti masing-masing memegang potongan puzzle, tetapi enggan menyusunnya bersama; bahkan kerap memaksakan potongan yang tidak selaras, yang pada akhirnya bukan menyelesaikan persoalan, melainkan menambah kerumitan baru.
Justru dalam kondisi tidak ideal ini sebenarnya nilai-nilai perjuangan NU semakin relevan. NU bukan hanya organisasi ulama terbesar. Sejak awal, NU ternyata adalah rumah besar umat. Di dalamnya tidak hanya para kiai, santri, ning, dan gus, tetapi juga pedagang kecil, petani, pelaku UMKM, akademisi, birokrat, teknokrat, hingga pejabat. Saya sendiri menyaksikan bagaimana jamaah NU di luar negeri, termasuk di Jerman, terdiri dari akademisi, pekerja industri, pengusaha, serta mereka yang tetap setia pada tradisi pengajian dan tahlilan. Alhamdulillah, berkat salah satu perjuangan almarhum Gus Dur, kemajemukan ini bukanlah hambatan kolektivitas, melainkan peluang besar yang mungkin belum sepenuhnya disadari.
Jika semua sektor ada di NU, bukankah seharusnya NU menjadi ruang kolaborasi lintas keahlian untuk bersama-sama menciptakan keadaan yang lebih baik?
Sebagai contoh, konsep SDGs (Sustainable Development Goals) yang kini banyak diterapkan di Jerman menawarkan visi global yang luhur dan relevan dengan asas Islam: pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, pekerjaan layak, dan keberlanjutan lingkungan. Namun di Indonesia, SDGs sering terasa hanya sebagai proyek laporan dan hiasan, bukan proyek kehidupan. Target KPIs (Key Performance Indicators) sering tercatat di atas kertas, tetapi dampaknya jarang benar-benar terasa di pasar tradisional, pesantren kecil, atau desa-desa yang jauh dari pusat kebijakan. Hal yang sama terjadi dengan kecerdasan buatan (AI): teknologi ini bukan sekadar tren atau alat mahal, melainkan sarana yang, jika dipahami dan digunakan dengan tepat, bisa mendukung pengambilan keputusan, transparansi, dan inovasi yang selaras dengan nilai sosial dan agama. Sayangnya, banyak kebijakan di Indonesia belum memanfaatkan AI secara strategis; AI hadir tanpa arah, SDGs dijalankan tanpa implementasi riil, keduanya sering hanya menjadi simbol, bukan solusi.
Sebagai jamaah NU yang terus memperdalam keilmuan di area SDGs dan perkembangan teknologi, saya melihat ada masalah di terbatasnya akses, keterhubungan, dan keterbukaan. Banyak ulama tentu tidak sepenuhnya menjalani praktik industri modern, rantai pasok global, atau memahami implikasi teknologi baru. Sebaliknya, banyak praktisi industri dan pelaku usaha tidak memahami kaidah halal-haram secara komprehensif, maqashid syariah, dan nilai keadilan sosial yang hidup dalam tradisi pondok, Islam NU. Akibatnya, kebijakan dan inovasi dakwah sering berjalan sendiri-sendiri, dan agama pun sering hanya dijadikan pedoman subyektif, padahal sebenarnya bisa menjadi dasar sistem yang terpadu.
Lebih ironis, kita sering terpesona dengan ide besar dari luar, seperti SDGs dan AI, tetapi melupakan nilai atau basis substansi yang harus tertanam secara kolektif. Perubahan nyata tidak bisa hanya bergantung pada satu atau dua orang; dibutuhkan pemahaman dan kerja bersama. Misalnya, dilema menyalahkan seorang polisi karena pungli ketika gajinya belum mencukupi, atau menuding pejabat korup tanpa memperhitungkan tekanan sistemik yang mereka hadapi. Di titik ini, setiap individu dihadapkan pada pilihan: ikut arus sistem yang salah dan menjadi bagian dari kerumitan, atau berani ikut menyusun potongan-potongan yang ada untuk membangun solusi. Tanpa kesadaran kolektif dan penanaman nilai yang nyata, usaha untuk mengubah sistem ke arah lebih baik akan selalu terbatas.
Padahal, fundamental NU sejak lama mengajarkan bahwa kebaikan sosial tidak lahir dari kesempurnaan sistem, tetapi dari ikhtiar manusia di tengah sistem yang sering dzalim, dan almarhum Gus Dur telah mencontohkan hal ini dengan keterbukaan pemikiran, berjiwa altruistik, dan gagasannya.
Di Jerman, saya menyaksikan bagaimana teknologi, termasuk AI, digunakan untuk mempermudah kehidupan: meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi data, pendidikan, dan industri. Teknologi dijadikan sarana inovasi yang nyata untuk kemaslahatan umat. Di Indonesia, politik dan hukum sering menjadi “lapangan permainan” sehari-hari, sering dibahas, dianalisis, bahkan diperdebatkan seolah itu bisa di-“inovasikan” oleh siapa saja. Padahal, area itu seharusnya berfungsi sebagai kerangka dan pedoman saja. Fokus pada praktik nyata, pemanfaatan teknologi, dan penanaman nilai sosial jauh lebih efektif untuk mendorong perbaikan kehidupan sehari-hari.
Indonesia masih berada di titik penentuan nasibnya. Nilai-nilai Islam sebaiknya Kembali dijadikan pedoman, bukan hanya status. Teknologi dan AI bisa menjadi alat untuk mendukung perbaikan. SDGs dapat dijadikan kerangka tujuan yang jelas, sehingga bisa memperbaiki layanan publik dan membuka peluang industri ekonomi baru. Tanpa nilai dan arah yang jelas, teknologi tetap mahal dan eksklusif hanya dinikmati segelintir orang.
Di sinilah peran NU menjadi sangat substansial. Dengan basis umat yang luas dan majemuk, NU memiliki modal sosial untuk menjadi penuntun etis bagi pemanfaatan teknologi dan inovasi, bukan sekadar simbol atau identitas. Bukan dengan menolak AI, tetapi dengan memastikan bahwa AI diarahkan pada kemaslahatan: transparansi, keadilan, dan tidak meninggalkan kelompok lemah dan rentan. Bukan dengan mendukung pemimpin zalim, tetapi justru mengarahkan dan mengingatkan.
Maka, NU, dengan seluruh keragaman aktornya, idealnya mampu mempertemukan dunia nilai dan praktik. SDGs bisa disisipkan sebagai kerangka tujuan bersama, sementara AI dan teknologi menjadi alat, bukan tujuan itu sendiri. Inilah visi yang saya lihat di NU Jerman dengan tagline pengurusnya: “tradition meets excellence”.
Integrasi ini bukan utopia. Di banyak komunitas NU di luar negeri, embrio ini mulai tumbuh: diskusi lintas disiplin, kajian etika teknologi, hingga inisiatif ekonomi berbasis nilai. Semua menunjukkan bahwa jalan itu ada; tinggal kemauan kita untuk berjalan bersama, dan sistem yang baik harus mendukung hal ini agar tidak berhenti hanya sebagai diskursus, tetapi sampai di level praktik, terutama dalam kebijakan, politik, dan jaminan ekonomi-sosial.
Optimisme yang saya maksud bukan sekadar retorika. Ia berakar pada tradisi Islam NU: tetap sabar tanpa gusar, tetap kritis tanpa sinis, dan tetap berbuat baik meski sistem problematik, sebagaimana ditunjukkan Gus Dur. Bagi orang kecil, pencari nafkah, optimisme berarti peluang nyata: akses keterampilan, industri stabil dengan diversifikasi, dan perlindungan sosial yang bermartabat. Bagi negara, optimisme berarti keberanian mengaitkan teknologi dengan nilai untuk efektivitas kebijakan, bukan sekadar mengejar tren global. Bukankah hati nurani kita seharusnya tergugah ketika melihat tetangga atau saudara sendiri masih banyak yang tinggal di gubuk, atau harus mencari makan dari tempat sampah? Perhatian pada sesama di negeri sendiri adalah bagian dari realisasi nilai dan tindakan nyata ajaran agama.
Jika kita mengingat kembali ajaran tokoh-tokoh NU, termasuk Gus Dur, pesan utamanya dalam humanisme dan Khittah NU selalu sama: kemanusiaan di atas segalanya. Gus Dur tidak membayangkan Islam sebagai alat kekuasaan atau perebutan jabatan politik, tetapi sebagai kekuatan moral yang merawat keberagaman dan martabat manusia.
Sebagai kesimpulan, NU Jerman sudah menerapkan mengintegrasikan asas SDGs dan AI. Asas agama dan teknologi bisa bertemu dalam satu jalan menuju kualitas dan kemakmuran. NU yang majemuk memiliki peluang besar menjadi jembatan antara nilai dan inovasi. Tantangannya bukan kemampuan, tetapi kemauan. Pertanyaannya sederhana: apakah kita bersedia berjalan bersama, saling melengkapi, dan mewujudkan cita-cita leluhur, masyarakat yang adil, bermartabat, dan sejahtera bersama? Sebaiknya kita segera buka kembali kitabnya, pelajari ilmunya, dan ingat nasihat Ulama agar kita tidak keliru dalam berpikir dan bertindak.
– Wa Allahu muwaffiq ilaa Aqwaami Thoriq.